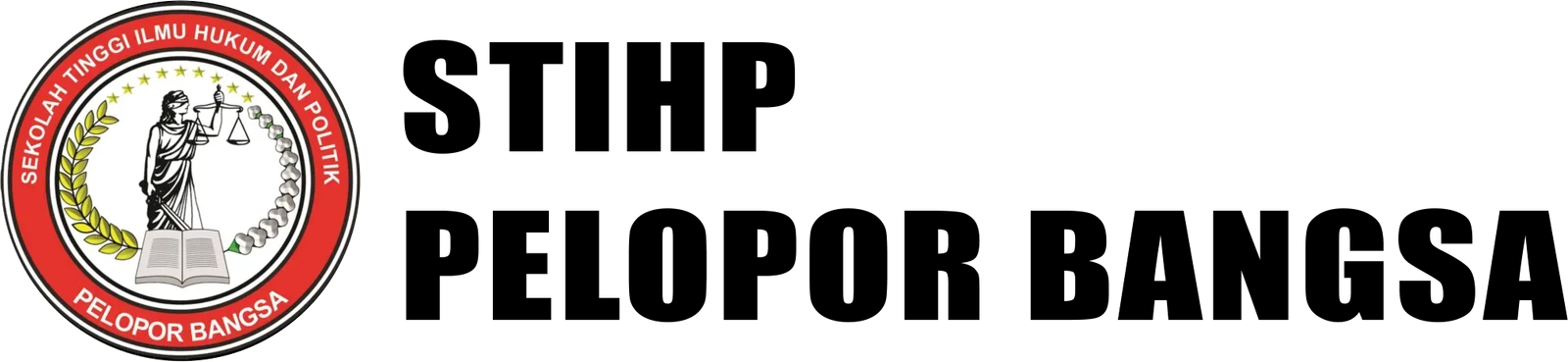Pertanyaan Quo Vadis (Ke mana engkau pergi?) menjadi sangat relevan ketika kita membahas masa depan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Sebagai payung hukum utama yang mengatur tata kelola sumber daya hutan di Indonesia, keberadaan UU Kehutanan kini berada di persimpangan jalan, menghadapi turbulensi signifikan akibat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law.
Artikel ini, yang disusun dari perspektif analisis kritis mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik (STIHP) Pelopor Bangsa, akan mengupas ambiguitas hukum yang muncul dari kebijakan Omnibus Law dan menelaah potensi dampaknya terhadap laju deforestasi serta keberlanjutan lingkungan di Indonesia.
Ambiguitas Normatif Pascaterbitnya Omnibus Law
Awalnya, UU Kehutanan 1999 didesain dengan semangat desentralisasi dan penguatan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Namun, kedatangan Omnibus Law Cipta Kerja membawa perubahan substansial melalui penghapusan, perubahan, dan penambahan pasal yang signifikan. Perubahan ini secara langsung menyentuh aspek-aspek krusial dalam tata kelola hutan.
Ambiguitas utama terletak pada pergeseran fokus dari aspek konservasi dan keberlanjutan menjadi aspek perizinan dan kemudahan investasi. Beberapa poin kritis yang menimbulkan kontroversi dan ambiguitas hukum meliputi:
- Perizinan Berbasis Risiko: Pengubahan dari sistem perizinan yang ketat menjadi perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 7). Hal ini dikhawatirkan dapat mempermudah izin pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kayu, berpotensi melonggarkan pengawasan terhadap batas-batas area yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan.
- Kriminalisasi dan Sanksi Administrasi: Perubahan mendasar dalam rezim sanksi, yang cenderung menggeser penekanan dari sanksi pidana ke sanksi administratif. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas efek jera (deterrence effect) dalam mencegah kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar atau illegal logging.
- Kawasan Hutan yang Belum Dilepas: Pengaturan pemanfaatan lahan di kawasan hutan yang telah terlanjur dimanfaatkan (misalnya untuk perkebunan) sebelum terbitnya UU Cipta Kerja. Meskipun bertujuan menyelesaikan konflik tenurial, mekanisme legalisasi ini dikritik karena dapat melegitimasi praktik perambahan hutan yang terjadi di masa lalu, termasuk yang dikategorikan sebagai Hutan Lindung.
Deforestasi dan Ancaman Terhadap Fungsi Ekologis Hutan
Deforestasi, yang didefinisikan sebagai penghilangan hutan permanen untuk diubah menjadi lahan non-hutan, merupakan isu kritis yang telah lama menghantui Indonesia, salah satu negara dengan mega-biodiversity terbesar di dunia. Ambiguas hukum yang tercipta oleh Omnibus Law berpotensi memperparah tren ini.
Pelonggaran prosedur perizinan dan sanksi dapat menjadi pendorong (driver) utama deforestasi dengan:
- Meningkatkan Kemudahan Akses: Investor, terutama dari sektor perkebunan dan pertambangan, dapat lebih mudah memperoleh hak pemanfaatan kawasan hutan dengan pengawasan yang longgar, mempercepat konversi hutan alam menjadi monokultur.
- Melemahnya Pengawasan: Ketika sanksi hukum berkurang tingkatannya, aparat penegak hukum di lapangan kehilangan taji untuk menindaklanjuti pelanggaran berat secara pidana, sehingga memberikan insentif negatif kepada pelaku kejahatan lingkungan.
Dampak yang paling nyata adalah terancamnya Fungsi Ekologis Hutan, yaitu kemampuan hutan untuk menyediakan jasa lingkungan vital, seperti regulasi iklim, perlindungan tata air, dan konservasi keanekaragaman hayati. Hilangnya hutan bukan hanya masalah hilangnya pohon, tetapi juga hilangnya kemampuan bumi untuk menyerap karbon, yang secara langsung berkontribusi pada krisis perubahan iklim global.
Perspektif Hukum dan Politik di STIHP Pelopor Bangsa
Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa, mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami bunyi pasal, tetapi juga menelaah implikasi politik dan filosofis di balik perubahan kebijakan tersebut. Analisis kritis kami berpusat pada dua konsep utama:
1. Konflik Kewenangan dan Sentralisasi
Omnibus Law Cipta Kerja dinilai membawa tren resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, terutama terkait penerbitan izin. Ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan dalam reformasi hukum sebelumnya. Dalam konteks kehutanan, pemerintah daerah yang berada di garis depan pengelolaan dan pengawasan hutan seringkali lebih memahami dinamika sosial dan ekologis lokal. Pengurangan peran mereka dapat menciptakan gap pengawasan dan memicu konflik tenurial baru.
2. Keseimbangan antara Ekonomi dan Ekologi
Inti dari perdebatan Omnibus Law kehutanan adalah upaya menyeimbangkan kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh investasi dengan tuntutan pelestarian lingkungan. Mahasiswa STIHP menyoroti bahwa pembangunan berkelanjutan harus menjadi prinsip utama. Pembangunan yang mengorbankan fungsi ekologis hutan untuk keuntungan jangka pendek pada akhirnya akan menciptakan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan (misalnya, melalui bencana alam dan hilangnya produktivitas lahan). Prinsip intergenerational equity (keadilan antargenerasi) menuntut agar generasi sekarang tidak menghabiskan sumber daya alam yang seharusnya dinikmati oleh generasi mendatang.
Untuk memastikan bahwa hutan tetap dapat berfungsi secara berkelanjutan dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, penting untuk memahami lebih jauh mengenai Hak Penguasaan Atas Tanah (HPAT). Mekanisme hukum ini perlu diperjelas agar tidak tumpang tindih dengan status kawasan hutan, terutama di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki pengetahuan lokal dalam konservasi.
Rekomendasi Mahasiswa untuk Masa Depan UU Kehutanan
Menghadapi ambiguitas hukum dan ancaman deforestasi, mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa merekomendasikan langkah-langkah kritis:
- Harmonisasi Hukum yang Jelas: Diperlukan regulasi turunan (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) yang secara eksplisit dan tegas menjamin bahwa semangat konservasi UU Kehutanan 1999 tidak dilemahkan oleh kemudahan investasi Omnibus Law.
- Penguatan Law Enforcement: Pengembalian sanksi pidana sebagai prioritas untuk kejahatan lingkungan berat, didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (Polhut, Penyidik PNS) dan sistem peradilan lingkungan yang efektif.
- Partisipasi Publik dan Transparansi: Mekanisme perizinan harus menjamin transparansi penuh dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dan organisasi sipil dalam pengambilan keputusan terkait alih fungsi kawasan hutan.
Jalan Menuju Hutan yang Berkelanjutan
Quo Vadis UU Kehutanan? Jawabannya terletak pada komitmen kolektif, terutama dalam merespons ambiguitas hukum yang ditimbulkan oleh Omnibus Law. Jika hukum gagal secara tegas memprioritaskan fungsi ekologis hutan, Indonesia berisiko kehilangan paru-paru dunianya dan menghadapi konsekuensi lingkungan yang tidak terpulihkan.
Melalui analisis kritis ini, STIHP Pelopor Bangsa menegaskan pentingnya hukum yang berpihak pada keberlanjutan. Masa depan UU Kehutanan harus mengarah pada penguatan perlindungan hutan sebagai warisan ekologis dan ekonomi bangsa, memastikan bahwa pembangunan yang kita kejar adalah pembangunan yang berakal, berkeadilan, dan bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.